Dua puluh tujuh tahun berlalu sejak Reformasi 1998 digulirkan. Tanggal 21 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai tonggak sejarah ketika kekuasaan otoriter Orde Baru runtuh, membuka jalan bagi demokratisasi, kebebasan sipil, dan harapan akan negara yang lebih adil.
Tetapi siapa yang benar-benar bisa merayakan reformasi hari ini, ketika masih begitu banyak pihak yang terus menanggung luka akibat ketidakadilan yang tak pernah diselesaikan? Bisakah keluarga korban penghilangan paksa, korban tragedi Semanggi dan Mei 1998, atau para aktivis HAM yang yang saban Kamis berdiri di depan istana, ikut merayakan sesuatu yang tak pernah benar-benar berpihak kepada mereka?
Pertanyaan itu menyentil kenyataan pahit. Bahwa sementara sebagian dari kita mungkin merayakan reformasi, banyak yang masih terperangkap dalam luka lama akibat janji-janji yang tak pernah ditepati.
Sejarah mencatat bahwa reformasi lahir dari darah dan air mata rakyat. Ratusan mahasiswa dan warga sipil gugur dalam benturan melawan militer dan polisi. Mahasiswa menduduki gedung DPR untuk menyuarakan reformasi total dan mendesak perubahan sistem pemerintahan yang dinilai sarat penyimpangan.
Ada enam tuntutan reformasi yang digaungkan mahasiswa saat itu. Amandemen UUD 1945, supremasi hukum, pemberantasan KKN, otonomi daerah, penghapusan dwifungsi ABRI, serta pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Sebagian tuntutan itu memang terealisasi. Militer ditarik dari parlemen, pemilu menjadi lebih terbuka, pers menjadi bebas, dan lembaga negara seperti KPK dibentuk.
Namun, kita tahu bahwa pencapaian reformasi hanya berhenti di ranah struktural. Secara prosedural, demokrasi Indonesia bisa dianggap berhasil. Pemilu berjalan, partai banyak, dan media hidup. Tapi secara substansial, demokrasi kita pincang. Politik dikuasai oligarki, hukum tebang pilih, korupsi masih merajalela, dan yang paling menyakitkan—negara masih gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Di sinilah letak kemunafikan reformasi. Negara mengeklaim telah berubah, tetapi masih menutup mata terhadap luka yang ia ciptakan sendiri. Aksi Kamisan, yang telah berjalan sejak 2007, adalah simbol dari kegagalan negara. Setiap Kamis, keluarga korban pelanggaran HAM—ibu-ibu, ayah, adik, dan rekan-rekan yang kehilangan orang tercinta dalam tragedi 1965, 1998, Talangsari, dan lainnya—berdiri diam di depan Istana Negara. Mereka membawa foto orang-orang yang dihilangkan, disiksa, dibunuh, atau dikriminalisasi oleh negara. Mereka tidak menuntut lebih dari yang seharusnya. Pengakuan, keadilan, dan pertanggungjawaban negara.
Namun hingga kini, suara mereka tetap diabaikan. Pemerintah silih berganti, tetapi komitmen terhadap penyelesaian pelanggaran HAM tidak pernah serius. Komnas HAM telah menyelidiki dan merekomendasikan berbagai kasus ke Jaksa Agung, tetapi tidak satu pun berujung di pengadilan. Bahkan, beberapa pelaku yang namanya jelas tercantum dalam laporan Komnas HAM justru mendapat tempat dalam pemerintahan. Ini bukan hanya ironi, tapi pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.
Lebih menyakitkan lagi, pemerintah justru menggunakan pendekatan simbolik tanpa substansi. Pada 2023, Presiden Joko Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, namun tidak disertai langkah hukum. Tidak ada penyidikan, tidak ada penuntutan, tidak ada pemulihan menyeluruh. Pengakuan itu menjadi kosmetik politik semata yang digunakan untuk memperbaiki citra, bukan menyembuhkan luka.
Memang benar pernah ada langkah yang diambil. Tetapi langkah-langkah ini justru lebih memperburuk keadaan daripada menyelesaikan masalah. Pemberian uang ganti rugi dengan catatan para korban harus tetap diam seribu bahasa.
Langkah lainnya dilakukan dengan memberikan informasi tempat di mana korban berada, namun sekali lagi, semuanya harus tetap jadi rahasia. Tentu saja, ini bukan hanya sekadar ketidaktepatan prosedur, melainkan upaya pembungkaman yang nyata. Banyak langkah yang entah kenapa diabaikan atau diproses dengan cara yang tidak transparan.
Di tengah semua ini, Aksi Kamisan tetap teguh. Mereka tahu bahwa suara mereka tidak populer, tidak diliput secara masif, tidak mendatangkan suara dalam pemilu. Tetapi mereka tetap berdiri. Karena dalam diam itulah mereka mempertahankan ingatan, melawan lupa yang dipelihara oleh negara. Mereka tidak mencari belas kasihan, tetapi menagih tanggung jawab negara yang selalu dijanjikan, tapi tak pernah ditepati.
Mengapa suara mereka seakan termarginalkan? Karena mereka berbicara tentang masa lalu yang tidak nyaman. Mereka menyodorkan cermin kepada negara yang lebih suka membanggakan “stabilitas” ketimbang keadilan. Dalam politik yang dibentuk oleh kepentingan elektoral, korban pelanggaran HAM bukan komoditas yang menguntungkan. Mereka tidak memiliki daya tawar politik, tidak punya modal finansial, dan sering dianggap hanya sebagai bayang-bayang masa lalu yang mengganggu citra masa depan.
Namun yang dilupakan negara adalah tidak ada masa depan yang utuh jika masa lalu terus ditutupi. Kita tidak bisa membangun keadaban politik jika fondasinya adalah impunitas. Reformasi bukan hanya tentang mengganti sistem, tetapi memperbaiki moral politik. Dan moral itu hanya bisa ditegakkan jika negara berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kekerasan yang pernah dilakukannya.
Hari ini, ketika kita melihat aktor-aktor lama Orde Baru kembali merajai panggung politik, kita patut bertanya. Apakah reformasi benar-benar berhasil? Ketika militer kembali aktif di ruang sipil, ketika suara rakyat dibungkam dengan UU ITE, ketika KPK dilemahkan, ketika pemilu dijalankan dengan manipulasi hukum—apakah kita masih bisa membanggakan diri sebagai negara reformis?
Aksi Kamisan menjadi pengingat bahwa kita hidup dalam demokrasi yang dikompromikan. Suara mereka adalah cermin nurani bangsa yang menolak tunduk pada kompromi politik yang melupakan keadilan. Mereka bukan sekadar korban, tetapi penjaga terakhir dari etika reformasi yang sesungguhnya.
Maka pada Hari Peringatan Reformasi ini, mari kita hentikan euforia seremonial dan mulai bertanya secara kritis. Siapa yang benar-benar diuntungkan oleh reformasi? Dan siapa yang terus menjadi korban dari janji-janji yang tak ditepati?
Reformasi sejati bukan soal mengganti pemimpin, tapi tentang mengubah cara negara memperlakukan rakyatnya. Selama keluarga korban pelanggaran HAM masih berdiri di Kamisan, maka kita belum pantas mengatakan bahwa reformasi telah selesai. Karena mereka yang berdiri diam di depan istana, tidak akan pernah berhenti, mempertanyakan kapan keadilan akan berpihak pada mereka.
Stevani Agustin
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

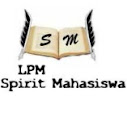
 Komentar
Komentar