Tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa. Ribuan mahasiswa, buruh, dan rakyat turun ke jalan, melawan rezim otoriter yang telah bercokol selama lebih dari tiga dekade. Teriakan “reformasi” kala itu bukan hanya slogan kosong, melainkan sebuah janji masa depan. Demokrasi, keterbukaan, serta hilangnya praktik kekerasan yang dilakukan negara terhadap rakyat.
Lalu, dua puluh tujuh tahun berselang, tepatnya pada 2025, kita dihadapkan pada pertanyaan yang getir. Apakah cita-cita reformasi itu benar-benar terwujud, atau justru kita sedang kembali tergelincir ke masa lalu yang kelam—masa represi?
Gelombang protes besar-besaran yang mengguncang Indonesia sejak akhir Agustus 2025 menjadi alarm keras. Rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Rp 50 juta per bulan di tengah krisis ekonomi membuat rakyat murka. Ironisnya, ketika rakyat masih berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang melambung, para elit justru sibuk menambah fasilitas pribadi.
Hingga puncaknya, kematian tragis Affan Kurniawan—seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun—yang tertabrak kendaraan taktis polisi dalam aksi demo, memantik kemarahan publik. Dari sinilah api perlawanan menyebar ke berbagai kota. Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Medan, hingga kota-kota lainnya.
Seperti tahun 1998, kini sejarah kembali terulang, jalan-jalan kembali dipenuhi lautan massa. Namun kali ini, respon negara bukan berupa keterbukaan, melainkan represivitas. Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat setidaknya lebih dari 3.300 orang ditangkap secara sewenang-wenang sepanjang 25–31 Agustus 2025 di 20 kota besar. Penangkapan itu tidak hanya menyasar peserta aksi, tetapi juga orang-orang yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Dari data yang sama, lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka dan sedikitnya 10 orang meninggal dunia.
Pada peristiwa itu, aparat menggunakan gas air mata, water cannon, bahkan kekerasan fisik untuk membubarkan demonstrasi. Seakan sejarah mengulang diri. Aparat, yang seharusnya menjadi pengayom, malah berperan sebagai algojo.
Lebih jauh, pemerintah tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan narasi. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers menyatakan bahwa sebagian tindakan demonstran “miring ke arah pengkhianatan dan terorisme.” Stigmatisasi semacam ini bukanlah hal baru. Di masa Orde Baru, oposisi kerap dicap “subversif” atau diberi label “PKI” untuk mendeligitimasi gerakan rakyat. Kini, label itu berganti rupa, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu membungkam suara kritis.
Di sinilah letak ironi besar Reformasi. Dua dekade lalu, rakyat menuntut agar militer kembali ke barak, agar politik bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan agar rakyat bebas bersuara tanpa takut ditangkap. Kini, tuntutan itu kembali menggema melalui gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ada 17 poin jangka pendek, mulai dari penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, hingga pembekuan kenaikan fasilitas DPR.
Lalu ada delapan poin jangka panjang, termasuk reformasi DPR, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi perpajakan, hingga pengembalian Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepenuhnya ke barak. Bila dilihat, ini bukan sekadar daftar teknis, melainkan pengulangan dari tuntutan reformasi 1998 yang belum pernah benar-benar tuntas.
Apakah artinya Reformasi gagal? Mungkin tidak sepenuhnya. Reformasi telah membuka ruang demokrasi. Pers bebas, partai politik beragam, dan pemilu langsung berjalan rutin. Akan tetapi naasnya, substansi demokrasi itu rapuh. Ia terjebak pada formalitas, sementara oligarki politik dan ekonomi masih bercokol. Reformasi memang berhasil menjatuhkan rezim lama, tetapi gagal menyingkirkan budaya lama. Budaya korupsi, budaya menindas, dan budaya elitis.
Apa yang kita saksikan hari ini adalah refleksi dari kegagalan tersebut. DPR yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru menjadi simbol kemewahan dan ketidakpekaan. Aparat yang seharusnya melindungi justru menindas. Pemerintah yang seharusnya mengayomi justru melabeli rakyat dengan stigma berat. Situasi ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan digunakan untuk menjaga stabilitas semu dengan menekan rakyat.
Namun, berbeda dengan masa lalu, kini rakyat memiliki medium baru: media sosial. Slogan-slogan kreatif, poster digital, dan narasi solidaritas menyebar cepat, menciptakan tekanan publik yang masif. Jika 1998 dimenangkan dengan radio kampus, pamflet, dan orasi jalanan, maka 2025 mungkin dimenangkan dengan kolaborasi antara jalanan dan dunia maya. Mahasiswa, buruh, influencer, bahkan warganet anonim saling bersatu dalam tagar dan seruan. Solidaritas inilah yang bisa menjadi kunci untuk mencegah Indonesia jatuh lebih dalam ke jurang represi.
Pertanyaannya, apakah pemerintah mau mendengar? Sejauh ini, responsnya setengah hati. Presiden memang membekukan beberapa fasilitas DPR dan menjanjikan investigasi, tetapi publik menilai langkah itu minim. Apa artinya pembekuan tunjangan jika nyawa rakyat sudah melayang? Apa artinya investigasi jika aparat yang menindas tetap bebas tanpa pertanggungjawaban? Reformasi 1998 lahir bukan dari janji setengah hati, melainkan dari tekad rakyat yang bulat. Maka, jika pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin 17+8 Tuntutan Rakyat akan menjadi lonceng Reformasi Jilid II.
Kita tentu berharap jalan itu tidak perlu ditempuh. Kita berharap pemerintah mau belajar dari sejarah, mau menghormati aspirasi rakyat, dan mau melakukan reformasi substansial. Tapi jika harapan itu pupus, maka rakyat akan kembali memilih jalan yang sama seperti 1998: turun ke jalan, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa, demi masa depan yang lebih adil.
Pada akhirnya, opini ini ingin menegaskan satu hal, demokrasi tidak pernah datang gratis. Reformasi 1998 adalah hasil darah dan air mata, pun demokrasi 2025 hanya bisa bertahan jika rakyat terus menjaganya. Jika kita diam, maka represi akan kembali menguasai. Jika kita apatis, maka sejarah akan berulang.
Dan ketika negara gagal menjaga rakyatnya, hanya ada satu hal yang tersisa: warga jaga warga. Solidaritas itulah benteng terakhir melawan represi, sekaligus harapan agar demokrasi tidak benar-benar mati. Karena pada akhirnya, bukan kekuasaan yang menyelamatkan bangsa ini, melainkan keberanian rakyat untuk saling menjaga.
S.A

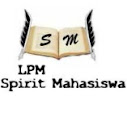
 Komentar
Komentar