Dua kali dalam dua bulan terakhir, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jurnalis—pertama dengan para pemimpin redaksi pada Februari, dan terbaru dengan tujuh jurnalistik senior di kediamannya di Hambalang, Sabtu (6/4). Sepintas, langkah ini terlihat sebagai upaya menjalin komunikasi dengan media. Namun jika dilihat lebih jeli, pola ini justru menunjukkan kecenderungan yang patut dicurigai: pengendalian media dengan metode yang lebih halus.
Berbeda dengan pendekatan represif ala Orde Baru—media dibredel, dibungkam, hingga dirusak dari dalam—apa yang kini terjadi berlangsung dalam kemasan yang lebih halus. Wawancara dibatasi, partisipan dipilih secara selektif, dan ruang tanya jawab spontan seperti doorstop dikendalikan, bahkan ditiadakan.
Saat laga Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), yang bertepatan dengan unjuk rasa besar pada awal Maret lalu misalnya, Prabowo hadir menonton pertandingan namun tidak memberi akses untuk sesi doorstop. Ini terjadi di tengah desakan publik untuk mendapat klarifikasi langsung atas berbagai isu yang mencuat. Keputusannya sekadar menonton bola dan mengabaikan massa aksi, disertai penghalangan jurnalis, mempertegas pola relasi kuasa yang menutup akses kontrol publik.
Pengaturan ini bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah bentuk penghalangan kerja jurnalistik, dan secara prinsip sudah melanggar semangat Undang-Undang Pers maupun hak publik atas informasi. Alasan yang kerap digunakan—menunggu momen tepat, menjaga suasana, atau keamanan—nyatanya terlalu sering berubah menjadi pola menghindar.
Narasi yang dibangun dalam wawancara dengan tujuh jurnalis pun terasa berat sebelah. Prabowo dalam pernyataannya mengaitkan media dengan adu domba, hoaks, bahkan pendanaan asing. Ia juga pernah menyampaikan peringatan untuk mewaspada media yang “ingin memecah belah bangsa.” Ungkapan-ungkapan semacam ini bukan saja menyesatkan, tetapi juga berbahaya. Ia membangun ketidakpercayaan terhadap pers di mata publik, yang pada akhirnya bisa melegitimasi pembatasan akses dan kebebasan pers.
Dalam kerangka yang lebih luas, gejala ini mencerminkan sebuah kecenderungan yang semakin kentara: civilphobia—ketakutan terhadap partisipasi sipil yang kritis. Ketimbang membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat, terutama elemen sipil yang kritis seperti jurnalis, aktivis, dan akademisi, pola komunikasi Prabowo lebih memilih jalur aman yang tertutup. Ia cenderung menghindari debat publik yang autentik, serta membatasi ruang-ruang spontan di mana kontrol narasi tidak bisa dijaga sepenuhnya. Ini bukan hanya bentuk kekhawatiran terhadap citra, tetapi kegamangan terhadap dinamika sipil yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan.
Jika dicermati secara utuh, kita sedang menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai soft repression: pembungkaman sipil lewat kontrol narasi, penyaringan akses, dan delegitimasi lembaga pers. Ini bukan praktik baru. Di masa lalu, kita menyaksikan bagaimana otoritarianisme bekerja secara terang-terangan. Kini, ia datang dengan wajah yang lebih santun, namun tetap dengan kuasa yang serupa.
Transparansi tidak diukur dari berapa banyak wawancara yang digelar, tetapi dari seberapa terbuka akses terhadap pertanyaan yang sulit dan suara yang kritis. Demokrasi bukan ditandai oleh jamuan media, melainkan oleh keberanian menghadapi kebebasan pers secara setara.
Jika pola ini dibiarkan, maka bukan hanya media yang dipinggirkan, begitu juga ruang sipil secara keseluruhan terancam dibungkam—perlahan, tetapi pasti. (stv/frd)

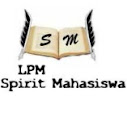
 Komentar
Komentar